[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

Umum kenali aku dengan
nama Bawi. Namun, sudah pasti, itu bukan nama sebenar aku. Tiada siapa tahu
nama sebenar aku. Malah, tiada siapa tahu latar belakang aku.
Dan ini adalah
kisah tentang diri aku.
Kalau ditanya
sejak bila aku terjerumus ke dalam kancah persundalan, aku dengan bangga akan jawab
sejak dari aku masih satu sel lagi. Lahir dalam sisi gelap pembangunan, aku
adalah anak lorong yang makan hasil lendir dari kerja ibu aku, seorang pelayan.
Aku sendiri tidak tahu siapa ayah aku, atau yang mana satu, tapi yang aku tahu,
aku hidup bersama dua orang perempuan; seorang ibu dan seorang kakak.
Walaupun ibu yang
melahirkan aku, tapi kasih sayang pertama aku datang dari kakak. Pada aku,
kakaklah yang memainkan peranan seorang ibu, sedangkan ibu hanya keluar pagi
dan balik tengah malam atas urusan ‘mencari sesuap nasi’. Beza umur sejauh
lapan tahun tidak pernah membuatkan hubungan kami adik-beradik berenggang.
Kakak menyayangi aku, menjaga aku dan mengambil berat tentang diri aku walaupun
kehidupan kami tidak pernah sinonim dengan perkataan ‘senang’ dan ‘mewah’. Kami
bahagia berdua.
“Maruah diri
adalah nombor satu. Tak kira betapa miskinnya kita, betapa hinanya kita di mata
orang lain, asalkan kita ada maruah, kita akan sentiasa bahagia.” Itulah
nasihat yang berkali-kali diingatkan kakak kepada aku.
Sewaktu aku
berusia tujuh tahun, di kala kanak-kanak sebaya aku sibuk pergi balik sekolah
menuntut ilmu, aku hanya bermain di tepian longkang. Ibu kata, aku masih kecil
untuk ke sekolah. Sedangkan aku tahu, masalah utama adalah duit pembelanjaan.
Ibu hanya mampu membiaya hanya seorang, maka dia memilih untuk menyekolahkan kakak.
Aku tidak kisah. Malah, aku lebih seronok. Dapat melihat kakak pulang dari sekolah
setiap tengahari, kemudian gigih menyediakan makan tengahari untuk aku,
sentiasa membuatkan aku tersenyum. Kakak cantik dalam pakaian seragam sekolah.
Kakak juga akan mengajar aku membaca dan menulis pada waktu petang sebelum aku keluar
bermain di taman permainan.
Suatu hari, aku
terdengar perbualan ibu dan kakak dari dalam bilik.
“Biar kakak
berhenti sekolah. Ibu sekolahkan adik pula. Kakak boleh cari kerja. Boleh bantu
ibu.” Ibu tanpa berfikir panjang menerima cadangan dari kakak. Beberapa hari
kemudian, aku dibawa ke sekolah untuk didaftarkan. Semuanya adalah jasa kakak
yang sanggup berkorban demi aku.
Selepas saat itu, kehidupan
kami berubah. Kakak keluar kerja dari pagi sehingga ke petang. Dia mendapat
upah dari kerja membersih dan membasuh pinggan mangkuk di sebuah restoran berdekatan.
Namun, kakak tetap akan mencuri masa tengahari untuk pulang dan sediakan makanan
untuk aku. Selalunya dia akan tunggu aku balik dari sekolah dan makan tengahari
bersama sebelum dia kembali ke tempat kerja. Walaupun masa aku bersama kakak
semakin berkurangan, tapi aku tetap gembira.
Ibu? Tidak
habis-habis dengan ‘kerja’nya dari pagi sehingga lewat malam melayan lelaki.
Satu hari, sewaktu
aku pulang dari sekolah, aku dapati rumah tiada orang. Tiada kakak. Tiada ibu.
Tiada makanan.
Beranggapan kakak
sedikit terlewat dari tempat kerjanya, aku menyorok di dalam almari pakaian di
dalam bilik kakak untuk mengejutkan dia sejurus selepas dia sampai di rumah
nanti. Beberapa ketika semasa aku sedang menyorok, aku terdengar suara kakak
dari pintu depan.
“Tak nak. Ibu,
tolonglah. Kakak tak nak!”
“Jangan degil. Kau
kata nak tolong ibu. Jadi tolonglah ibu.”
Suara kakak dan
ibu bergilir-gilir memecah suasana. Tapi dari bunyi langkah kaki, aku percaya masih
ada seorang lagi di situ. Kawan ibu barangkali.
“Tak nak. Ibu,
tolonglah!” Suara kakak makin kuat. Dari celahan almari, aku mengintai keluar.
Kelihatan ibu sedang menarik tangan kakak masuk ke dalam bilik kakak di mana
aku sedang bersorok. Lalu ibu menolak kakak tertunduk di atas katil. Mata kakak
merah, berair mata. Turut kelihatan, seorang lelaki yang tidak dikenali sedang
menghembus asap rokok dari sudut bilik, memerhati kelakuan ibu dan kakak sambil
tersenyum.
“Aku tak peduli.
Kau kata nak tolong aku, jadi kau kena buat,” ibu mendesak kakak. Belum sempat
kakak membuka mulut, pipinya dihinggap satu penampar dari ibu.
“Jangan buat aku
marah!” Ibu mengugut. Kakak menggosok pipinya yang kesakitan, hanya berdiam
diri di atas katil sambil teresak-esak menahan tangis.
Ibu menuju ke arah
lelaki tadi dan berbisik sesuatu yang tidak dapat aku dengari. Lalu lelaki itu mengeluarkan
sejumlah duit kertas biru yang berlipat dari kocek seluarnya dan memberikan
duit tersebut kepada ibu. Ibu, dengan senyuman, mengambil duit itu dan dengan
segera keluar dan menutup pintu bilik. Si lelaki itu pula menanggalkan butang
baju kemejanya satu persatu sambil menghampiri kakak. Kakak merayu agar dia
dikasihankan tapi lelaki itu terlalu leka dengan fikiran kotornya.
Seterusnya, hanya
sejarah. Aku menyaksikan segala-galanya, bagaimana pakaian kakak disentap, kudrat
kakak dinafi, pekikan kakak diabai, maruah kakak dirampas, dan seterusnya kakak
longlai tidak terdaya berseorangan. Aku mahu membantu, tapi entah kenapa aku
tidak mampu bergerak. Aku tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya mata sibuk menatap
tidak berkelip seluruh kejadian sambil ditemani air yang tidak berhenti mengalir
keluar. Ini adalah pemandangan yang tidak mungkin dapat aku lupakan.
Niat aku mahu
mengejutkan kakak bertukar dengan aku yang dikejutkan. Kakak aku kini sudah
tidak bermaruah. Maruah yang dijaganya sekian lama. Maruah yang dikatanya
paling penting untuk bahagia. Kini, maruah itu sudah tiada.
Sejak hari itu,
kakak jadi pendiam. Kakak tidak seramah dulu, termasuk ketika bersama aku.
Setiap kali aku melihat wajah kakak, tiada ekspresi yang kakak tonjolkan. Aku
tahu kenapa, tapi aku tidak mahu mengatakannya. Aku hanya diam.
Bila melihat ibu,
aku berasa jijik. Di sekolah diajar ungkapan ‘ibu mana tidak sayangkan anak’,
namun di hadapan aku ada bukti sebaliknya. Haruan makan anak. Harapkan pegar, pegar
makan padi. Dia bukan lagi ibu aku. Pada aku, ibu sudah mati, dan aku tidak
keberatan untuk merealisaikannya.
Beberapa hari
selepas peristiwa hitam itu, sewaktu aku balik rumah dari sekolah, aku dapati
makanan tengahari sudah disediakan. Aku tersenyum gembira. Semua ini bermaknanya
kakak ada di rumah. Kami akan makan bersama, ketawa bersama, riang bersama
kembali.
Kami akan bahagia
seperti dulu.
Sewaktu aku ke
dalam bilik kakak untuk memanggilnya makan bersama, terdapat satu lagi pemandangan
yang tidak dapat aku lupakan. Kakak, dengan lidah terjelir panjang, mata
terbeliak dan merah padam, tergantung dengan satu hujung tali terjerut di leher
dan satu lagi terikat di siling bilik. Jasad tidak bernyawanya terbuai-buai
ditiup angin yang datang dari tingkap yang terbuka. Di atas meja, bertindihkan
buku, terdapat satu nota tertulis, ‘maruah kakak hilang, kakak tiada pilihan.’
Sekali lagi, aku tidak
mampu berbuat apa-apa. Aku terkaku.
Kakak membuat
keputusan menamatkan riwayat hidupnya.
Pada aku, kakak seorang
yang lemah.
Hanya kerana
maruahnya dirampas, kakak ambil keputusan untuk merampas kebahagiaan aku. Kakak
mengambil keputusan untuk menamatkan hayat satu-satunya orang yang aku sayang. Kakak
mengambil keputusan untuk menamatkan hayat dirinya sendiri. Adakah kakak tidak
memikirkan tentang apa yang akan terjadi kepada aku selepas dia pergi? Dia
tidak layak menentukan apa yang patut dia ambil dari aku. Tanpa kakak,
bagaimana aku mampu mengecap kebahagiaan lagi?
Ibu pula, hanya sehari
selepas pengebumian (yang diuruskan oleh ahli masjid berdekatan atas tuntutan
fardu kifayah), dia menyambung kerja persundalannya. Tiada masa untuk berkabung.
Tiada masa untuk meratap. Tiada masa untuk bersedih. Tiada masa untuk aku.
Sedangkan semua ini berpunca dari dia sendiri.
Dek kerana kematian
adalah satu kebiasaan di kawasan kejiranan itu, tiada siasatan susulan untuk
kematian kakak. Maka, ibu terlepas begitu sahaja. Masih lagi menjadi hamba
kepada nafsu, wang dan lelaki.
Pada waktu itu,
aku sedar, semua perempuan dalam dunia ini lemah. Kakak lemah, ibu pun lemah. Aku
tekad, aku akan rampas sebanyak mungkin maruah perempuan yang aku mampu,
sebagaimana mereka merampas seluruh kebahagiaan dan kegembiraan aku yang tidak
mungkin lagi akan berganti.
Setelah berpuluh
tahun merampas maruah perempuan, kini, aku bersama Galah, rakan sepenjenayahan dalam
bidang pelacuran. Kami sedang berada di pinggir hutan memperkemas pakaian seragam
polis yang kami pakai selepas merampasnya dari dua anggota yang kami serang
sebentar tadi.
“Macam mana
sekarang, Bawi? Polis tengah buru kita. Budak-budak tu dah terlepas. Kita sudah
menculik, membunuh, menyerang anggota polis lagi. Mati kita, Bawi. Ke tali
gantung kita.” Galah bernada cemas.
Aku tajam menatap
sesuatu di hadapan.
“Selagi aku tak
rabakkan budak perempuan tu, selagi aku tak penggal kepala budak lelaki tu, aku
tak akan puas. Maruah aku adalah nombor satu.”
Di sebalik
kegelapan senja, aku dan Galah sedang berdiri di dalam semak sambil memerhati dari
jarak hampir 50 meter perbuatan seorang pemandu lori pikap yang mengangkat dua
tubuh manusia masuk ke dalam lorinya. Selepas beberapa ketika, lori pikap itu
berlalu pergi tanpa sempat aku dan Bawi berbuat apa-apa.
“Mereka takkan
terlepas.”


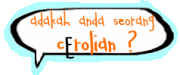

0 nota kaki:
Post a Comment